Andai Ayah tahu, banyak kisah yang mau kuceritakan saat ini. Aku rindu Ayah. Tidak hanya Ayah, aku juga rindu bunda. Belaian yang berarti kini tak ada lagi. Benarlah susah bertemu Ayah. Tetapi bunda, sungguh mustahil.
Oleh. Nashwa Ibtisam
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Payoda tebal menjuntai di langit. Bergerak dengan sarayu. Sang bagaskara tak kuasa meneroboskan baswara. Hingga hujan turun membasahi tanah. Menciptakan petrikor yang menenangkan. Tetesan air yang jatuh dari daun pohon cemara, membuat kubangan kecil berlumpur. Di antara pegunungan yang permai, sebuah keadaan mengiris lara mewarnai hari itu. Dama gundah berputar seperti roda. Mengungkap jamanika dunia.
Derap langkah kaki segerombolan orang terdengar semakin jelas. Bejana besi tertenteng rapi dibawa. Hujan tak menyurutkan langkah mereka untuk pergi. Ada payung yang meneduhkan. Dari jauh, terlihat ibu-ibu dengan jubah hitam berjalan ke arah rumah kayu bertingkat. Di dalam rumah, tergelar karpet hijau. Tamu-tamu yang telah datang duduk melingkar berjarak. Seorang gadis dengan muka basah memerah, tak kuasa menahan tangis. Sedikit saja dialihkan perhatian, kejadian itu seperti menghantui. Terkhusus ketika kabar dari rumah sakit datang memberitakan kabar meninggalnya bunda. Di samping anak perempuan itu berada, seorang ayah dengan hati goyah, berusaha sepenuh tenaga menguatkan anaknya.
Kisah yang diceritakan, merasuk dalam dada para pelayat. Gadis dengan perawakan gemuk nan tinggi itu terpenggal-penggal kala bercerita. Air mata menggantung dalam bulu mata lentiknya. Ia tak bisa menatap jelas. Pandangannya menjadi buram tertutup genangan air mata. Kerabat di dekatnya, menggenggam tangannya dan mengelus-elus pundak. Berusaha menguatkan. Kini, suasana menjadi sendu.
Silih berganti para tetangga dan kerabat datang sekadar mengucap belasungkawa pada Santi atas kepergian sang ibunda karena terserang virus Corona. Virus ganas itu telah sampai di pedesaan terpencil. Bunda yang sabar, bunda yang lembut, akhirnya tumbang setelah berjuang melawan virus yang makin merajalela.
“Sabar, ya, Santi.” Begitulah yang diucapkan para pelayat yang datang untuk menguatkan Santi yang terlihat makin rapuh.
Tiga hari berturut-turut, kediaman Santi dan ayah masih ramai. Lewat tiga hari, hanya ada dua atau tiga orang yang datang. Mereka adalah para kerabat yang tidak dapat hadir di hari sebelumnya.
Di malam yang hening, ayah Santi mengajak berbincang di balkon. Balkon yang tersusun dari kayu tampak sangat antik. Gaya arsitek kesukaan Santi dipesan khusus dari arsitektur ternama. Ayah dan Santi duduk berdampingan di sofa biru. Memandangi langit malam yang dipenuhi bintang tanpa terhalang polusi cahaya. Bintang gemintang membentuk rasi-rasi yang menakjubkan, dan sebagian berpencar.
“Santi, anakku. Selamanya kita tidak akan terus terpuruk dalam kesedihan. Tidak akan selamanya putus asa. Anakku, janganlah berlarut-larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, dengan kita kembali semangat dalam menjalani hidup ini, niscaya bunda akan senang dan tenang di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.” Ayah berbicara dengan suara bergetar. Air matanya basah, tidak dapat disembunyikan. Hatinya terasa kosong. Ada sesuatu yang hilang.
Santi bersandar di kursi sofa. Tangannya menyangga dagu. Sesekali ia mengusap air mata yang jatuh. Pesan ayah bermakna besar baginya.
“Sekarang kita merasa ada yang kosong. Benarlah, ayah pun begitu. Tetapi jangan sampai kita merasa sendiri, dan hidup menjadi beban untuk kita. Sesungguhnya, Allah bersama kita. Selalu. Setiap waktu, setiap saat. Santi lihat bintang-bintang di langit itu?” Ayah menunjuk bintang-bintang dengan cahaya terang. “Seterang cahaya bintang itu, kalau kita dalam lingkup polusi cahaya, maka bintang itu tidak akan bisa kita lihat. Santi, sejatinya Allah selalu bersama kita. Tetapi kita sendiri yang terkadang merasa tidak ada siapa-siapa yang membersamai kita. Polusi dalam hati kita perlu disingkirkan. Maka, kedamaian mutlak ialah ketika merasa Allah bersama kita.”
Santi hendak menjawab. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa mengangguk.
“Kita buat yang terbaik di dunia ini, Santi. Kita bersama, ya, buat bunda bahagia.”
Kata terakhir yang disampaikan ayah, sangat membangkitkan semangat Santi. Walaupun Santi sudah berada di kelas dua SMA, tetap saja hatinya akan rapuh bila mengalami kejadian pilu. “Iya, Yah,” Santi berkata lirih.
Ayah dan Santi kemudian melanjutkan pembicaraan tentang ke mana Santi harus melangkah untuk menata masa depan yang lebih baik. Walaupun kita tahu, manusia hanya bisa berencana. Hasil akhir, Tuhanlah yang menentukan.
***
Benar-benar di luar dugaan. Semalam langit cerah dipenuhi bintang-bintang. Kini gerimis datang bertandang menyapa pagi yang bimbang. Di dapur, Santi belajar memasak ditemani sang ayah. Tiba-tiba gawai ayah Santi berdering. Santi menoleh pada ayahnya. Kemudian ayah menjauh ke ruang sebelah untuk menerima panggilan dari kantornya. Ayah Santi terkejut. Ia mendengar kabar yang tidak mengenakkan. Hari ini juga, ia harus berangkat ke Ibu Kota untuk menjalankan tugas sebagai dokter. Rumah Sakit Joyolelono membutuhkannya. Banyak dokter yang terserang virus Covid-19 membuatnya harus menggantikan tugas mereka. Sementara, ayah Santi masih berkabung, rasanya tidak mungkin meninggalkan anak semata wayangnya sendiri di rumah. Diajak pun tidak memungkinkan.
Setelah menata hati dan mengontrol emosinya, ayah Santi kembali ke dapur membantu putri kesayangannya yang akan merampungkan menu sarapan pagi. Raut muka ayah Santi sekali waktu tampak gelisah walaupun sudah berusaha disembunyikan.
Sarapan hari ini dengan kare ayam. Sebelum ayah berkomentar tentang rasanya, Santi berceloteh lebih dulu. “Aa, ini pas banget rasanya! Ya kan, Yah?”
“Apa iya? Enggak kurang ...,” Ayah menatap sayur kare ayamnya.
“Hayo, kurang apa, Yah? Kalau enggak tahu, tandanya memang tidak kurang, ‘kan?” Santi tertawa ringan. Ia kembali ceria sedia kala.
“Ee, iya sih, pas.” Akhirnya ayah mengakui.
Santi yang menunggu komentar ayah, langsung menjentikkan jarinya. “Tuh, ‘kan!”
Selesai mereka makan, ayah hendak memulai pembicaraan tentang isi telepon tadi. Ia ragu, dan tidak ingin membuat suasana hati Santi semakin rapuh. Tetapi, bila tidak disampaikan, itu justru menjadi hal yang sangat buruk. Tidak mungkin ia berangkat tanpa berpamitan pada putri satu-satunya yang baru ditinggal ibundanya menemui Sang Khalik.
Santi yang tengah menyiapkan peralatan sekolahnya, berhenti sebentar karena panggilan ayah. Ia menghampiri ayah, dan duduk di sebelahnya.
“Santi, sudah siap dengan peralatan sekolahmu?”
“Sudah, Yah, sudah lengkap,” jawabnya sembari membetulkan posisi duduknya, agak meringkuk ke depan dengan tangan menggenggam.
“Kabar ini tidak mengenakkan bagi kita berdua. Ayah juga berat untuk mengatakannya.”
Mendengar hal itu, Santi tidak dapat berpikir kembali. Sudah jelas masalahnya sangat tidak mengenakkan untuk didengar. Ia menyandarkan diri ke kursi dengan wajah sedih.
Pelan-pelan dan berhati-hati ayah bicara pada Santi. “Ayah harus pergi ke Ibu Kota, dokter di sana benar-benar membutuhkan bantuan ayah.”
“Santi di sini sendiri, Yah?” tanya Santi tidak percaya.
“Iya, Santi lanjutkan pendidikan di sini.”
“Hah? Lagi pula, apa tidak ada dokter selain Ayah yang bisa menggantikan?” Santi mengerutkan dahi. Tangannya dilipat di depan dada.
“Semua dokter yang menguasai bidang ini, dikerahkan. Termasuk ayah. Di Ibu Kota, kasus melonjak berkali-kali lipat ditambah banyak dokter yang tumbang terserang virus. Karena itu, banyak dokter di daerah yang ditarik ke pusat. Ayah akan lakukan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang.” Ayah menatap penuh perhatian pada Santi. Ia menghela napas panjang.
“Berapa lama sih, Yah?” Santi penasaran.
“Entahlah. Kita berharap keadaan cepat pulih seperti sedia kala,” jawab ayah.
“Tuh, ‘kan. Pasti lama,” seloroh Santi.
Ayah tidak dapat merespons apa yang dikatakan Santi. Ada benarnya juga, sebab pandemi yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, berkisar tiga sampai lima tahun.
“Ayah berangkat kapan?” Santi penuh rasa khawatir ditinggal ayahnya.
“Ayah berangkat hari ini, Santi.”
“Hari ini?”
Ayah mengangguk. “Santi hari ini izin dulu sajalah. Besok masuk sekolahnya.”
"Iya, iya. Tentu saja," tanggap Santi dengan gugup.
"Baik, ayah buatkan surat izin." Ayah berdiri mengambil kertas untuk menuliskan surat izin. Santi menitipkan surat itu pada temannya untuk izin di saat sekolah daring ini.
Beberapa waktu setelahnya, ayah langsung bersiap diri. Sedangkan Santi, ia merasa diduakan. Mereka lebih penting daripada dirinya. Tetapi, bagaimanapun juga, ia akan tetap membantu ayahnya berkemas. Ia sedikit mengesampingkan egonya walau terasa berat. Karena ayah, adalah cinta satu-satunya yang tersisa.
Siang hari, pukul 11, ayah dan Santi berangkat dengan mobil pikap yang di belakangnya berisi penuh sayuran untuk diangkut ke Kota Kabupaten. Sampai di stasiun, Santi membantu menurunkan barang bawaan ayah. Beberapa orang membawa tas tenteng tidak terlalu besar ataupun tas punggung. Berbeda dengan Ayah yang membawa koper dan tas-tas kecil yang ditali menjadi satu.
Mereka masuk melewati pintu stasiun yang tinggi, peninggalan Belanda yang tak lekang oleh waktu. Hanya warna cat yang berganti. Sebelum ayah berbaris dalam antrean menuju loket, ia menyempatkan bicara pada Santi. “Ayah berjanji, akan menelepon Santi bila ada waktu luang. Ayah akan berusaha menyempatkan, Nak.”
Mata Santi berkaca-kaca sembari mencium tangan ayah. Dia tidak mau belahan jiwanya kosong lagi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lambaian tangan yang berat dilaku antara anak dan ayah yang baru saja berkabung. Kini harus berkabung kembali karena perpisahan. Santi masih berada di tempat. Menatap punggung ayah yang sedang mengantre, sampai samar-samar terlihat dari jauh, ayah masuk ke dalam gerbong kereta.
***
Sehari-harinya, Santi mengawali pagi dengan ibadah dan bersih diri. Lantas, Ia harus menyiapkan kebutuhan memasak. Terkadang, ia akan menyempatkan diri untuk membeli kebutuhan yang kurang. Ayah selalu mengirimkan uang dari Ibu Kota untuk keperluannya. Setelah itu, ia akan memasak sendiri. Di sela-sela menggoreng, ia menyempatkan untuk membuka buku pelajaran. Hari-hari ujian sekolah, menambah beban baginya. Santi harus benar-benar membagi waktu. Ia mengulang-ulang membaca untuk memahami pelajaran, kemudian membalikkan badan, melanjutkan menggoreng ikan. Ia menyiapkan sarapannya, dan meletakkannya di meja makan. Tidak langsung duduk makan, ia membawa buku pelajarannya juga ke meja makan. Sembari makan, ia juga membaca buku. Langkahnya kini cepat seakan tergesa-gesa. Ia benar-benar ingin menghemat waktu.
Berada di depan laptop melaksanakan pembelajaran secara online, melepaskan penatnya dari pekerjaan rumah. Tetapi otaknya harus bekerja dengan keras. Selepas sekolah pun, ia tidak bisa berhenti sejenak. Pasti akan menyapu lebih dulu, merapikan kamar, dan dilanjut mandi. Ia tidak tahan dengan debu, sebab itu rumah harus bersih selalu. Sore harinya, tanaman di depan rumah seakan meraung-raung, meminta air. Santi harus menyiram sebelum layu.
Tanggung jawab terhadap dirinya juga tidak dapat dikesampingkan. Ia akan masak untuk yang kedua kalinya. Hanya pada pagi dan malam ia akan masak. Selepas makan malam dan mencuci piring, ada tugas rumah dari sekolah yang perlu dikerjakan. Satu hal lagi yang tidak bisa ditinggalkan, ialah mengunci pintu rumah, dan mengecek semua jendela untuk dikunci. Santi merasa terbebani dengan tugas-tugas yang tidak ada habisnya ini. Susah untuk fokus dikala banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Alhasil, pekerjaan menjadi berantakan dan tidak maksimal.
“Duh, penuh sekali pikiranku, harus melakukan inilah, itulah. Sepertinya karena ini nilai ujianku jadi turun drastis. Ah! Kenapa bisa begini?” Santi mengeluh dengan tatapan kosong ke depan.
Suatu ketika di malam sebelum hari bahagia. Santi membayangkan masa depannya buram. Siapa yang akan menjembataninya untuk melanjutkan pendidikan? Tidak ada bayangan yang memuaskan. Hatinya perih kembali. Lantas Santi tidak memiliki bayangan selain ingin bertemu ibunda. Satu-satunya kebersamaan yang ia rindukan selama ini. Dalam duduknya di meja belajar, diambil sebuah pena. Dibukanya buku diary, ia akan bercerita segalanya di sana.
Kini aku, tidak segigih dulu. Rasanya, aku tidak bisa menjamin masa depanku cerah. Aku kesepian. Beban hidup sudah lebih dari cukup. Melewati batas rata-rata kemampuanku. Benarkah hidup selalu begini? Ah, nyatanya satu tahun berlalu, hari-hariku selalu begini. Bagaimana mungkin besok tidak seperti ini? Mustahil, mustahil, mustahil. Besok adalah hari bahagia. Salah satu hari paling bahagia. Tetapi lihatlah besok, 'hari paling bahagia' hanya sebatas julukan.
Kepala rasanya pecah berkeping-keping. Sekalian saja bukan? Buah biji dari bunga terompet sudah terjuntai di depan rumah. Tidak perlu banyak hal yang perlu dikorbankan. Itu saja, sudah bisa mengakhiri hidupku. Aku menanti pertemuanku dengan bunda. Aku akan pergi meninggalkan beban tak berarti. Aku akan pergi dari bayang-bayang masa depan. Lihatlah hari esok. Bila benar-benar seperti hari biasa, aku akan meminum seteguk dengan biji bunga terompet. Lihatlah besok. Lihat!
Santi segera menutup buku hariannya, dan membiarkan tergeletak di tengah-tengah meja belajar. Ia langsung menghempaskan badan ke kasur. Hanyut dalam kekalutan malam.
Ia seakan bertaruh dengan hari esok.
***
Ditemani rintik hujan yang membasahi taman, dan kabut mulai turun. Di depan, terlihat samar bukit-bukit dengan pohon pinus dan pohon cemara. Sore ini ia termenung di balkon kesayangannya. Sweet seventeen yang harusnya penuh bahagia, sepertinya akan terlewati begitu saja.
“Hari yang sepi. Sangat hampa. Janji tidak sesuai janji. Kebersamaan apa yang Ayah maksud?" tanya Santi dalam hati.
Sudah satu tahun ayah pergi ke Ibu Kota. Demi menjalankan tugasnya. Padahal, nyawa menjadi taruhannya. “Ayah lakukan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang.” Begitu katanya.
Pun kini, ayah justru yang terkena virus. Santi kesal dengan sikap ayahnya, meninggalkannya sendirian. Menurutnya, lebih baik ayah tidak pergi ke Ibu Kota kalau pada akhirnya terkena virus. Di sisi lain, Santi benar-benar tidak menginginkan kejadian satu tahun yang lalu terulang kembali.
Dalam hati Santi bergumam, “Andai Ayah tahu, banyak kisah yang mau kuceritakan saat ini. Aku rindu Ayah. Tidak hanya Ayah, aku juga rindu bunda. Belaian yang berarti kini tak ada lagi. Benarlah susah bertemu Ayah. Tetapi bunda, sungguh mustahil.”
Bibirnya bergetar, berzikir agar tidak merasa sendiri. Allah benar-benar selalu membersamai. Berkelabut dalam pikiran Santi, cerita teman-temannya saat hari ulang tahun sweet seventeen. Tidak lain pasti bersama orang tuanya. Terkhusus di masa pandemi ini, orang tuanya berada di rumah. Bekerja dari rumah. Sehingga dapat menyempatkan untuk kebahagiaan anaknya. Sedangkan ayah Santi?
Santi merasa iri. Ia menangis sesenggukan. Berharap pada Allah, sesuatu yang membahagiakan akan datang pada hari ini—hari paling penting dalam hidupnya. Tiba-tiba, handphone di sebelahnya berdering. Ia merasa enggan untuk mengangkat. Suaranya pasti serak parau. Diliriknya gawai merah itu, tampak pada layar, ayah menelepon.
“Ayah?” Santi tak percaya. Sebetulnya, ia kesal pada ayah. Tetapi, ia benar-benar menduga, ayahlah yang menjadi orang pertama mengucapkan selamat ulang tahun. 16 tahun sebelumnya, ayah dan bunda tidak pernah melupakan hari berbahagia itu.
Dengan terburu-buru ia segera mengangkat telepon video itu. Santi melihat, sepasang selang masuk ke dalam hidung ayah. Kemudian ayah mencoba melepas nebulizer, alat bantu seperti masker kaca yang menutup mulut dan hidungnya. Ayah berkata dengan terpatah patah, “Selamat ulang tahun, Santi. Semoga Allah memberkahimu selalu.” Ayah tersenyum sangat menenteramkan. Hati Santi terketuk seketika. Ia sudah terlampau meremehkan ayah.
“Terima kasih, Ayah. Ayah cepatlah sembuh. Santi rindu Ayah. Satu tahun tanpa Ayah itu seperti berjuta-juta tahun.” Setelah berucap, Santi menangis deras. Ayah hanya melambaikan tangan. Tampak dokter membantu ayah menutup nebulizer. Setelah itu, dokter meminta izin pada Santi untuk menutup telepon videonya.
Gadis manis itu terenyuh, ia benar-benar membuang jauh pikirannya untuk mengakhiri hidup. Bahkan ayah masih bertahan dan semangat walau dalam masa-masa kritis, Santi justru menyerah. Ia benar-benar merasa, ada cinta ayah yang tak tergantikan. Santi menjadi satu-satunya harapan keluarga.
Harapan hidup kembali semula. Ia ingin lebih dekat dengan ayahnya, dan menyuapkan makanan kesukaan ayah. Tetapi itu hanya akan menjadi sebatas khayalan. Ia berpikiran akan memberikan makanan pada tetangganya, sebagai ganti dari keinginannya itu. Sepertinya ayah akan merasa bahagia. Ia disambut baik oleh tetangganya. Santi diajak berbincang walau tidak dalam jarak dekat. Bahkan karena itu pula, ia selalu disapa di setiap pagi melalui jendela rumahnya.
“Dik Santi!” senyumnya merekah sembari menyiram tanaman di depan rumah.
Tidak lagi Santi merasa kesepian. Walaupun berbeda jauh rentang usia, tetapi itu bukan penghalang untuk berinteraksi. Rupanya, ia perlu terbuka dalam ranah yang seharusnya.
Pada akhirnya, Santi telah melewati masa kritisnya. Masa kritis yang menjadi masalah besar dan umum pada remaja sepertinya. Beruntunglah ia masih memiliki ayah yang cinta padanya. Tidak meninggalkan begitu saja. Rasa jenuh dalam keseharian terkadang memiliki arti kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Keterbukaan tentu tidak dilarang, selama dalam batasannya.[] TAMAT
Disclaimer
www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com








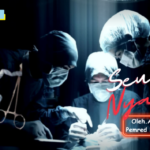


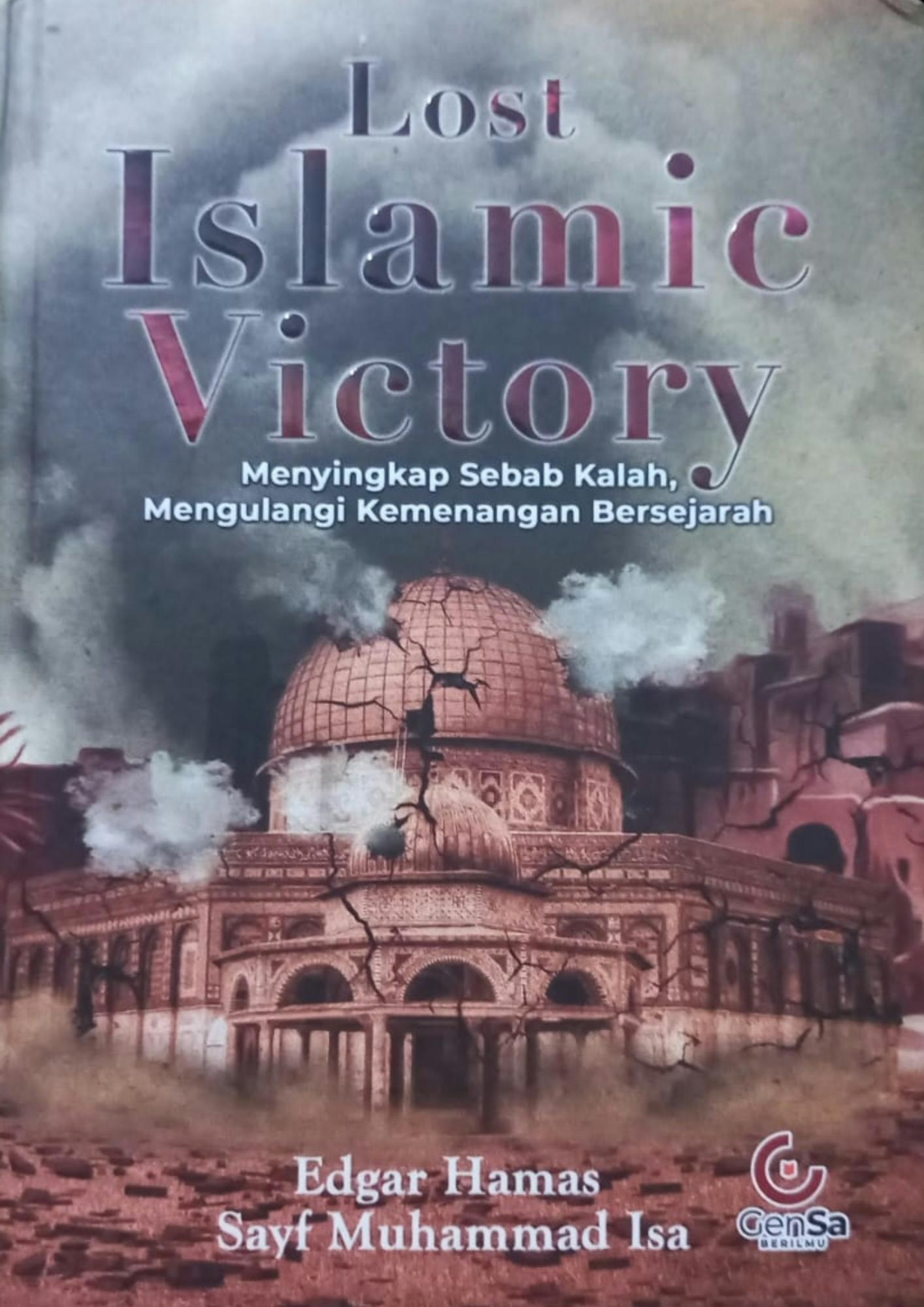

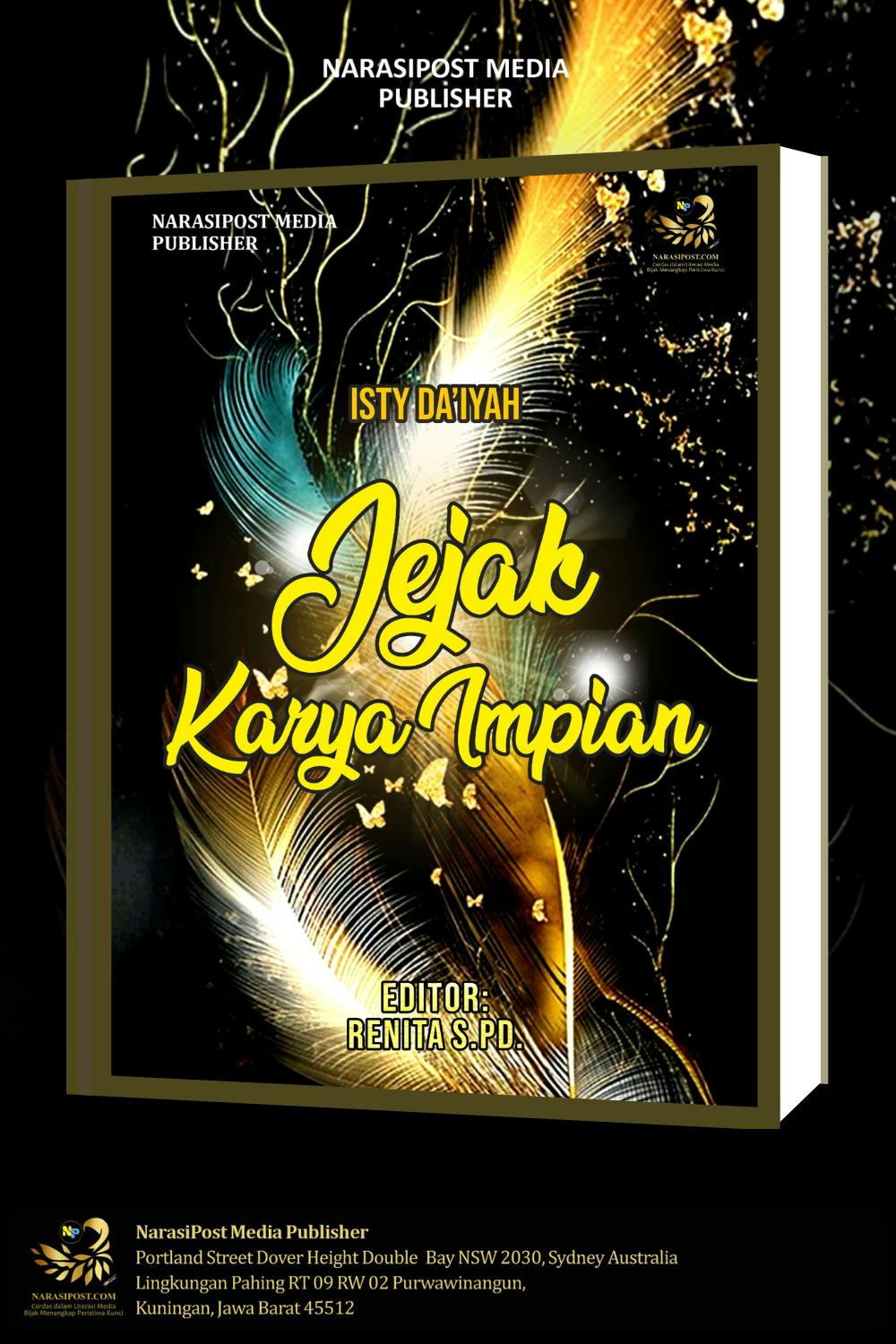

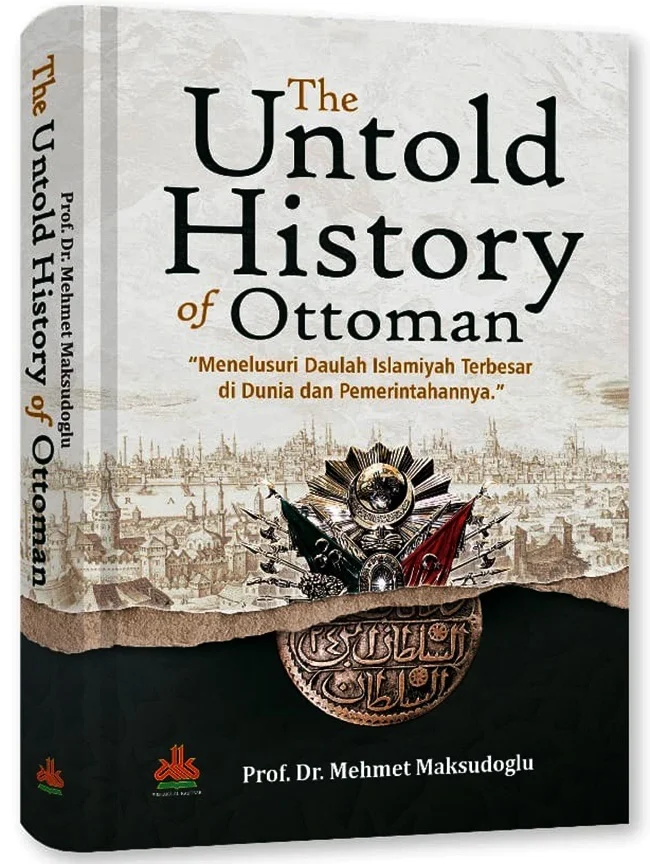

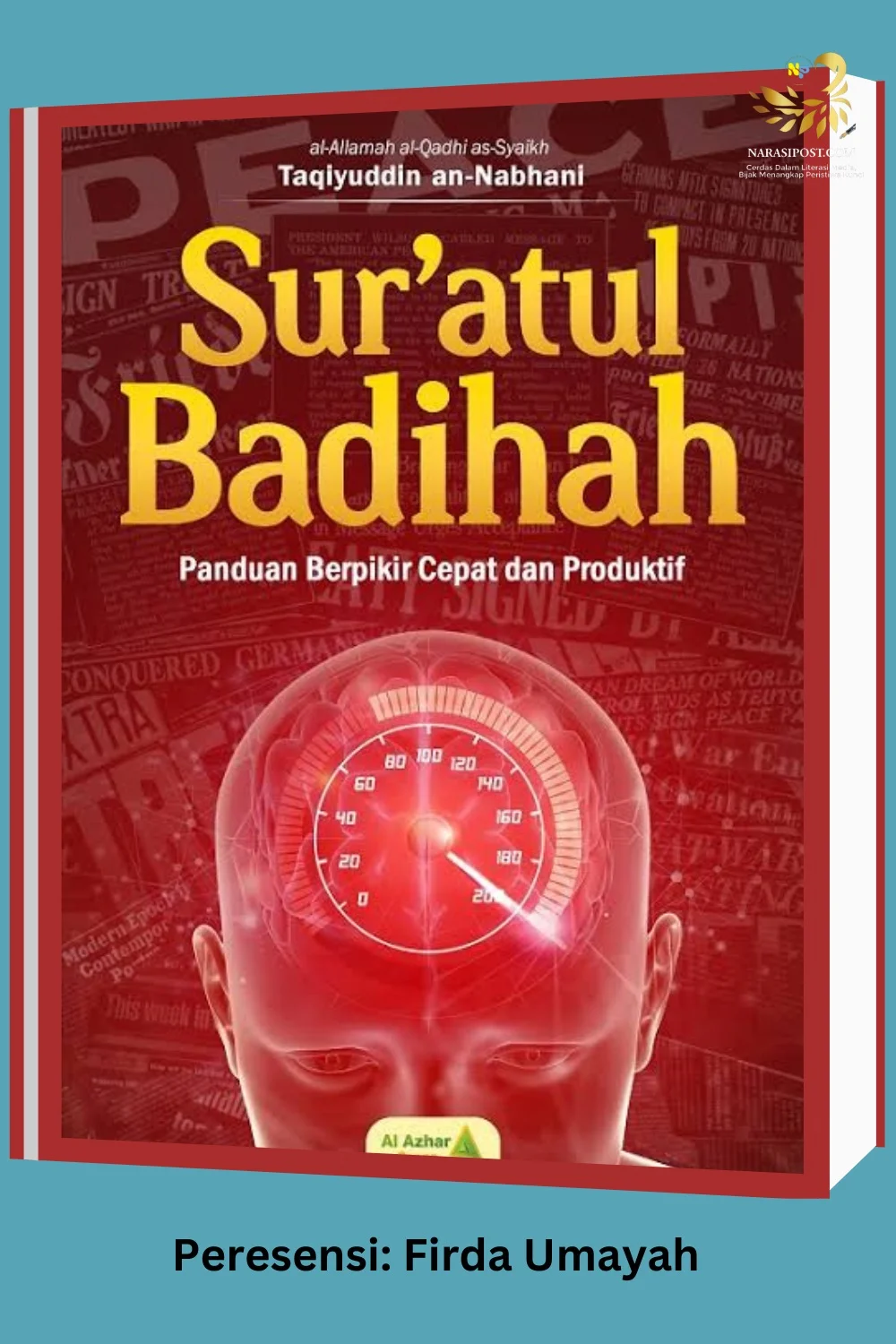

MasyaAllah, Santi gadis tegar yang ditinggal bundanya. Lalu ayahnya harus pergi untuk mengabdikan dirinya sebagai dokter di luar kota. Sendirian mendekap sepi.
Cerpen yang sastranya berkelas. Barakallah...
Ya memang kadang kita susah melupakan dan bangun dari berbagai pengalaman hidup yang diakami. Namun semua harus terlewati. Masyaallah kisah Santi menjadi gadis yang harus kuat menghadapi kesedihan hidup yang dijalani. Menguras hati terhanyut dalam cerita. Alhamdulillah karya yang keren
terbayang seperti apa ditinggal mati sang bunda.. pengalan masa SMA dulu, ayah pergi meninggal di rumah sakit.. setelahnya, terasa sedih dan sepi..
Naskah keren, ceritanya bikin nyesek. Banyak realita yg sama saat pandemi kemarin, anak2 ditinggal orang tua, orang tua kehilangan anak
MasyaAllah keren cerpennya. Kisahnya membuat hati ini turut terbawa suasana, ya pandemi Covid-19 banyak yang jadi korban.
Naskahnya keren. Nggak di dunia nyata, nggak di cerita, kalau temanya kehilangan dan kesepian itu bikin nyesek ya. Membayangkan kalau itu adalah diri kita. Barakallah ...
Jadi flashback ke masa-masa itu. Pandemi covid-19. Ada banyak kehilangan.
Jadi ingat tiga tahun yang lalu pun ikut terpapar..
Ceritanya bagus. Inget alm. Mamah, hebat ya Santi bisa melewati ujian di usia yang kritis masa-masa sekolah.
Barakallah ..
Bagus sekali cerpennya,, aroma sastra sangat tinggi,,5%
Maaf kepencet 5%, si kecil ikutan nimbrung
Dari awal sastranya sudah terasa, sampai harus mencari tahu kata yang belum saya pahami. Ternyata ini kisah ketangguhan seorang anak. MasyaAllah, cerpen yang keren.
[…] https://narasipost.com/challenge-np/08/2023/dalam-kubangan-cahaya-temaram/ […]
[…] Baca: dalam-kubangan-cahaya-temaram/ […]