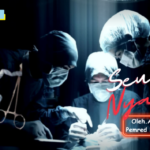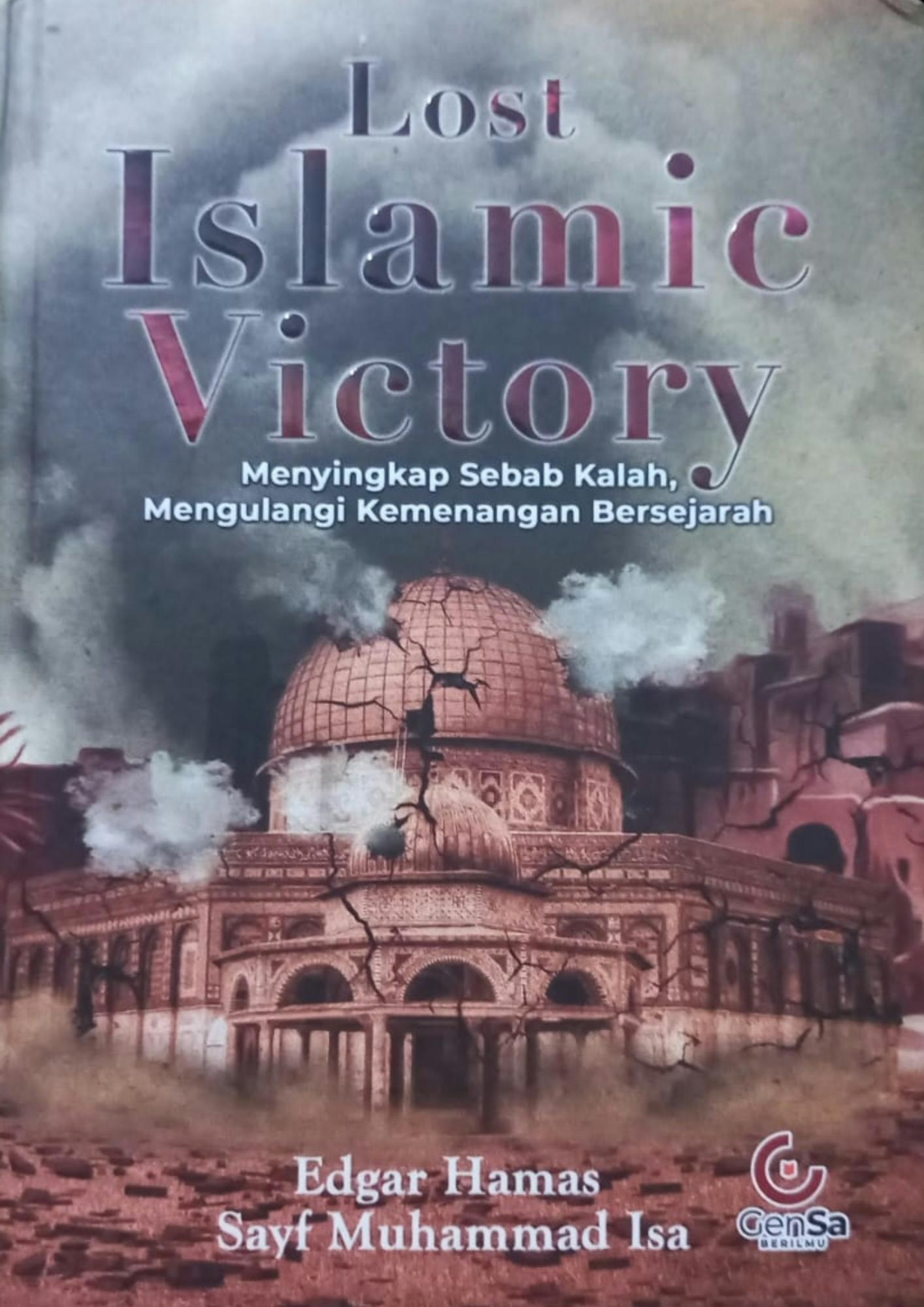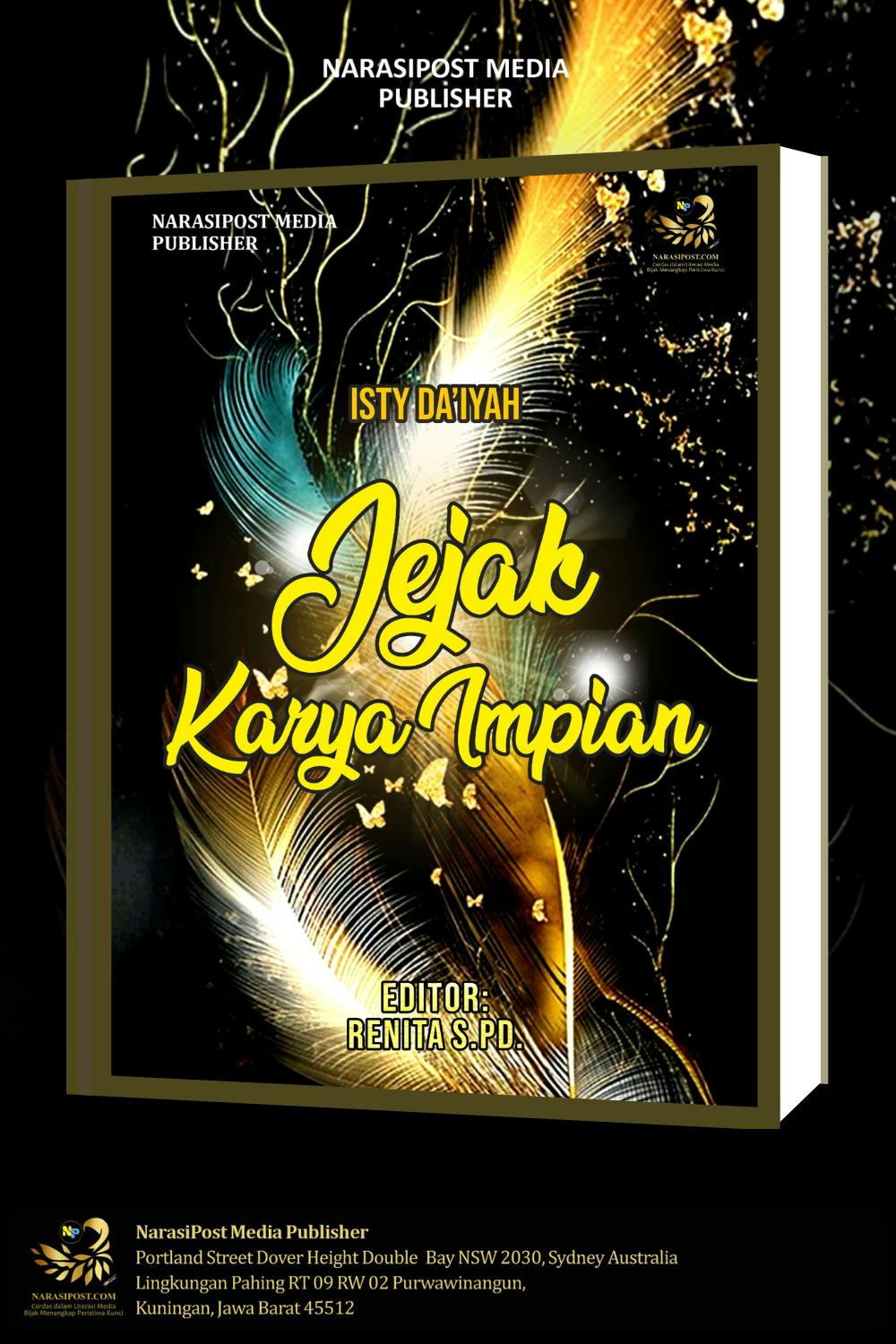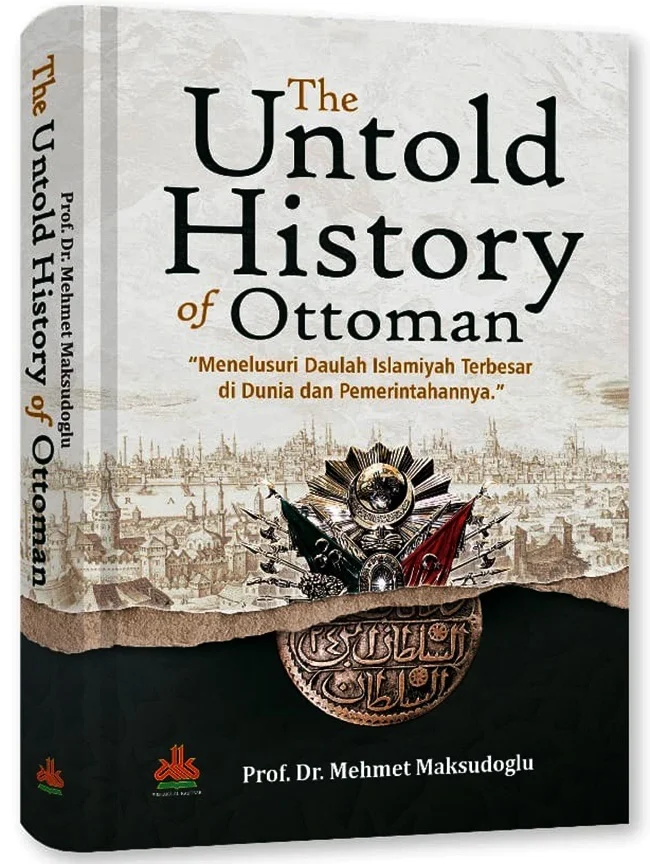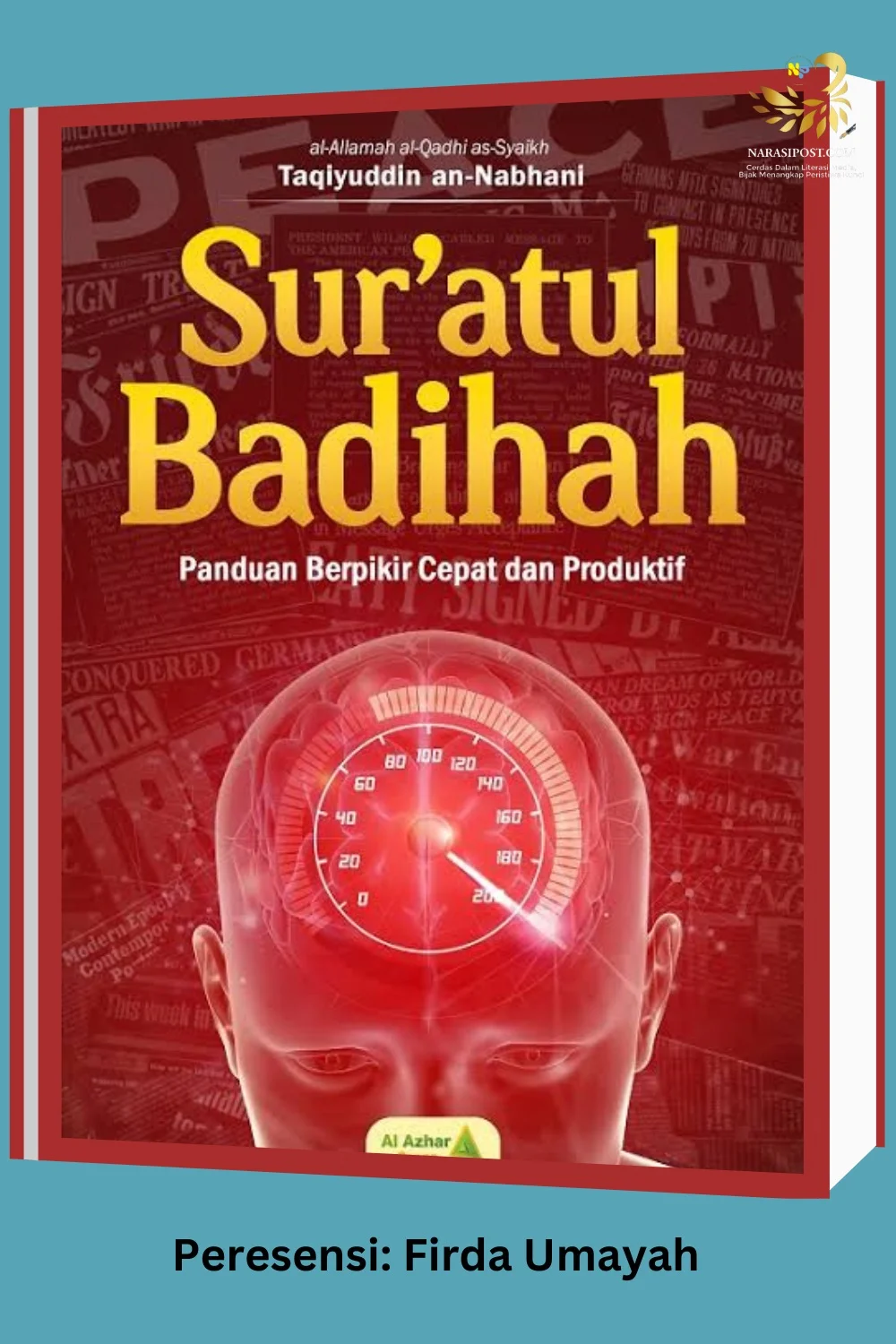“Krisis di Korsel ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan alternatif sistem yang mampu menjawab kelemahan mendasar sistem demokrasi kapitalis.”
Oleh. Haifa Eimaan
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
Narasiliterasi.id-Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menggunakan "topeng" demokrasi saat mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Akibat keputusan sepihaknya itu, Presiden Yoon diduga melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun kejaksaan menyatakan presiden memiliki kekebalan hukum, tetapi tuduhan pengkhianatan atas negara tidak dilindungi oleh konstitusi. Artinya, dalam kasus ini, sang presiden tidak memiliki kekebalan hukum. Karena itu, kasus ini tetap bisa diselidiki. Hasilnya, Presiden Yoon pun resmi menjadi tersangka. (cnnindonesia.com, 10-12-2024)
Atas keputusan sepihaknya memberlakukan darurat militer, Yoon telah meminta maaf kepada publik. Ia mengakui tindakannya telah menyebabkan kegaduhan besar dan menarik perhatian dunia. Oleh sebab itu, Presiden Yoon menyatakan dirinya siap mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Ia juga memasrahkan nasibnya kepada partai pendukungnya yakni Partai Kekuatan Rakyat.
Pada tanggal 7 Desember lalu, parlemen mencoba memakzulkan Presiden Yoon. Namun, upaya itu gagal karena tidak mencapai kuorum. Boikot dari anggota Partai Kekuatan Rakyat menjadi penyebab tidak tercapainya kuorum ini. Walaupun demikian penyelidikan tetap berlanjut.
Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu negara panutan demokrasi di Asia, kini menghadapi ujian berat. Apakah sistem mereka mampu memperbaiki diri dan menjamin keadilan? Ataukah ini menjadi sinyal bahwa demokrasi kapitalis sebenarnya memiliki cacat bawaan yang tersembunyi di balik topeng-topengnya?
Topeng Darurat Militer Korsel
Peristiwa dramatis yang menimpa Presiden Yoon Suk Yeol menandakan titik balik penting dalam sejarah demokrasi di Korea Selatan. Dalam episode yang nyaris memicu krisis konstitusional, Yoon memberlakukan darurat militer secara mendadak, mengepung parlemen dengan dalih melawan kekuatan yang disebutnya sebagai "antinegara". Tindakan ini merupakan ekspresi frustrasi politiknya terhadap parlemen yang dikuasai oposisi. Koalisi oposisi di parlemen dianggap oleh Yoon sebagai penghalang berbagai agenda pemerintahannya.
Tekanan politik luar biasa segera mengemuka. Sebagai akibatnya, ratusan demonstran turun ke jalan, menuntut pencabutan darurat militer. Lebih lanjut, bahkan partai pendukung Yoon sendiri, yakni Partai Kekuatan Rakyat, turut mengecam tindakannya sebagai kesalahan besar. Di sisi lain, pemimpin oposisi Lee Jae-myung dengan tajam menilai langkah presiden sebagai "ilegal dan inkonstitusional", mempertegas krisis legitimasi yang dihadapi Yoon.
Reaksi sistemis dan cepat dari parlemen Korea Selatan menunjukkan kerapuhan rencana Presiden Yoon. Dalam hal ini, mereka sepakat menolak status darurat militer. Oleh sebab itu, tidak heran bila dalam waktu kurang dari enam jam, seluruh anggota legislatif yang berjumlah 190 orang menyatakan ketidaksetujuannya. Lebih lanjut, Ketua Majelis Nasional, Woo Won Shik, dengan tegas menyebut tindakan presiden tersebut tidak sah. Ia juga menambahkan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi demokrasi. Akhirnya, militer pun mundur dari gedung parlemen sebagai bentuk ketaatan mereka pada proses demokrasi. (time.com, 3-12-2024)
Apa yang dilakukan oleh Presiden Yoon mengingatkan kembali pada era kelam pemerintahan otoriter Korea Selatan di tahun 1980-an. Peristiwa ini membangkitkan trauma kolektif masyarakat akan masa-masa represi. Kasus darurat militer yang diumumkan sepihak oleh Presiden Yoon Suk Yeol ini menyingkap banyak persoalan. Tidak hanya soal penyalahgunaan kekuasaan dan tuduhan pengkhianatan, tetapi juga memperlihatkan sisi lain dari sistem demokrasi berbasis kapitalisme yang selama ini dianggap ideal.
Sisi Gelap Sistem Demokrasi Kapitalis
Dari beragam model sistem pemerintahan saat ini, sistem demokrasi sering dipuji, bahkan dianggap paling ideal untuk diterapkan. Akan tetapi, kasus Presiden Yoon Suk Yeol makin mengungkapkan beberapa kelemahan sistemis dalam praktik demokrasi.
Pertama, polarisasi politik yang ekstrem mencerminkan keterpecahan sistem demokrasi di Korea Selatan. Perbedaan ideologis antara eksekutif dan legislatif tidak diatasi melalui musyawarah, melainkan dengan konfrontasi tajam. Presiden Yoon secara terang-terangan menuduh oposisi sebagai "pasukan antinegara," sementara pihak oposisi merespons gencar dengan mendorong pemakzulan. Kegagalan upaya pemakzulan pada 7 Desember 2024, semata-mata karena aksi dukung-mendukung antarpartai oposisi dan boikot dari partai pendukung Yoon.
Kedua, rapuhnya mekanisme checks and balances dalam kekuasaan. Meskipun terlihat solid dan memukau, mekanisme ini sebenarnya mudah digoyang oleh kepentingan politik sempit. Kemudahan Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 yang berlangsung kurang dari enam jam sebelum ditolak parlemen, menegaskan betapa rentannya mekanisme checks and balances ini.
Sistem demokrasi yang seharusnya menjunjung checks and balances, sering kali justru menjadi alat bagi elite politik dan ekonomi untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuasaan presiden dalam menetapkan keputusan besar seperti darurat militer, tanpa konsultasi atau mekanisme pengawasan yang memadai, menunjukkan lemahnya kontrol terhadap pemimpin tertinggi. Hal ini jelas berbahaya karena kebijakan sepihak seperti itu mampu menghancurkan tatanan masyarakat dan membahayakan stabilitas negara.
Topeng Demokrasi di Sistem Gagal
Dari kasus Presiden Yoon ini, makin tampak nyata kerusakan sistem demokrasi kapitalis. Sistem yang selama ini dipuja-puji sebagai yang terbaik ternyata hanyalah topeng untuk menutupi kebusukannya. Sistem ini ada hanya untuk melanggengkan kekuasaan sekelompok elite. Keberadaan mereka ini tidak lebih dari sekedar parasit masyarakat.
Rakyat ditipu dengan ilusi partisipasi, dipaksa bermain dalam drama politik yang sudah direkayasa. Setiap pemilihan senyatanya hanyalah pertunjukan untuk melegitimasi kekuasaan kapital. Benak rakyat dilambungkan dengan retorika kebebasan, padahal sejatinya mereka hanya alat untuk mengabdi pada kepentingan korporasi.
Aslinya sistem ini telah gagal, yakni gagal memberi keadilan, melindungi rakyat, dan gagal menjadi instrumen perubahan. Demokrasi kapitalis hanyalah dalih “halus” bagi para tirani kapital yang menyamarkan penindasan struktural di balik prosedur pemilu dan retorika kebebasan.
Krisis demokrasi yang terjadi di Korsel makin memperlebar ruang diskusi tentang alternatif sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, Islam sebagai sebuah sistem kehidupan memiliki Khilafah. Sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam, Khilafah pernah memimpin peradaban selama 13 abad. Kegemilangan peradabannya tidak perlu diragukan lagi. Sampai kini, masih banyak bukti sejarah akan kejayaannya.
Krisis ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan alternatif sistem yang mampu menjawab kelemahan mendasar demokrasi kapitalis. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah sistem pemerintahan berbasis Islam, yaitu Khilafah.
Keunggulan Akuntabilitas Khilafah
Dalam hal kepemimpinan dan akuntabilitas, Islam memiliki perspektif berbeda dengan sistem demokrasi.
Pertama, dalam Islam tidak ada polarisasi politik, seorang khalifah yang pengangkatannya melalui mekanisme baiat, bukan berdasarkan kepentingan partai. Khalifah wajib mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Allah. Ia juga bukan sosok yang memiliki kekuatan dan kekuasaan absolut, melainkan raa’in dan junnah yang memiliki kewajiban memelihara segenap kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya.
Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari jalur Abu Hurairah. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu ibarat perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan adil maka dengannya dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, dia pun akan mendapatkan azab karenanya.”
Kedua, checks and balances. Keputusan khalifah diawasi oleh mahkamah mazhalim yang independen, berbeda dengan checks and balances demokrasi yang sering tunduk pada kepentingan politik.
Akuntabilitas seorang khalifah tidak sekadar prosedural, tetapi berdasarkan syariat Islam. Masa kepemimpinan seorang khalifah tidak dibatasi jangka waktu tertentu seperti di sistem demokrasi. Selama khalifah senantiasa menjalankan syariat Islam; menerapkan hukum-hukumnya; mampu melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab Kekhilafahan maka ia tetap sah menjadi khalifah.
Seorang khalifah dapat diberhentikan jika ia kehilangan satu dari tujuh syarat in’iqad. Di dalam kitab Ajhizah Ad-Daulah Al-Khilafah terbitan Dar Al-Ummah karya As-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, ketujuh syarat-syarat itu adalah muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka, dan memiliki kemampuan menjalankan amanah Kekhilafahan. Apabila didapati seorang khalifah tidak bisa memenuhi satu dari tujuh syarat ini, ia tidak boleh terus menduduki jabatan khalifah. Adapun pihak berwenang untuk menetapkan pemecatannya adalah mahkamah mazhalim.
Peran Istimewa Mahkamah Mazhalim
Mahkamah mazhalim berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat, termasuk sengketa antara warga negara dengan pemerintah, bahkan dengan khalifah sekalipun. Lembaga ini memiliki tingkat independensi yang tidak dimiliki oleh sistem demokrasi, baik dalam hal kelembagaan maupun pengambilan keputusan.
Salah satu keistimewaan sistem peradilan Khilafah adalah keberadaan qadhi mazhalim yang dapat memproses kasus berdasarkan temuannya sendiri tanpa perlu adanya penggugat. Qadhi mazhalim bertugas mengawasi para pejabat dan implementasi hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat dan mencegah penindasan terhadap rakyat. Untuk menjamin independensi qadhi mazhalim, khalifah tidak berwenang memberhentikannya, terutama saat sedang menangani kasus yang melibatkan khalifah, mu’awin, atau qadhi al-qudhat.
Berbeda dengan sistem di Barat di mana presiden dapat membatalkan keputusan pengadilan, dalam sistem Khilafah, konsep "pengampunan" atas kejahatan tidak berlaku. Kejahatan dalam Islam adalah pelanggaran hukum syarak hingga harus diselesaikan sesuai takaran syariat. Keputusan qadhi mazhalim, walaupun berbeda dengan khalifah, sifatnya tetap mengikat. Keputusan itu harus dijalankan oleh segenap lembaga Khilafah. Khalifah tidak mempunyai kewenangan untuk mengurungkan keputusan tersebut dan wajib menaatinya. Khalifah tidak perlu bersembunyi di balik topeng ketaatan demi mempertahankan jabatannya sebab ia bertanggung jawab pada Allah Swt.
Penutup
Kasus di Korsel ini makin menegaskan kelemahan demokrasi kapitalis dalam menjamin keadilan dan stabilitas politik dalam negeri. Sebaliknya, dengan akuntabilitas berbasis syariat dan keberadaan mahkamah mazhalim, khalifah senantiasa berfokus untuk melayani umat dan menyejahterakannya.
Wallahu'alam bisshawab.[]
Disclaimer
www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com